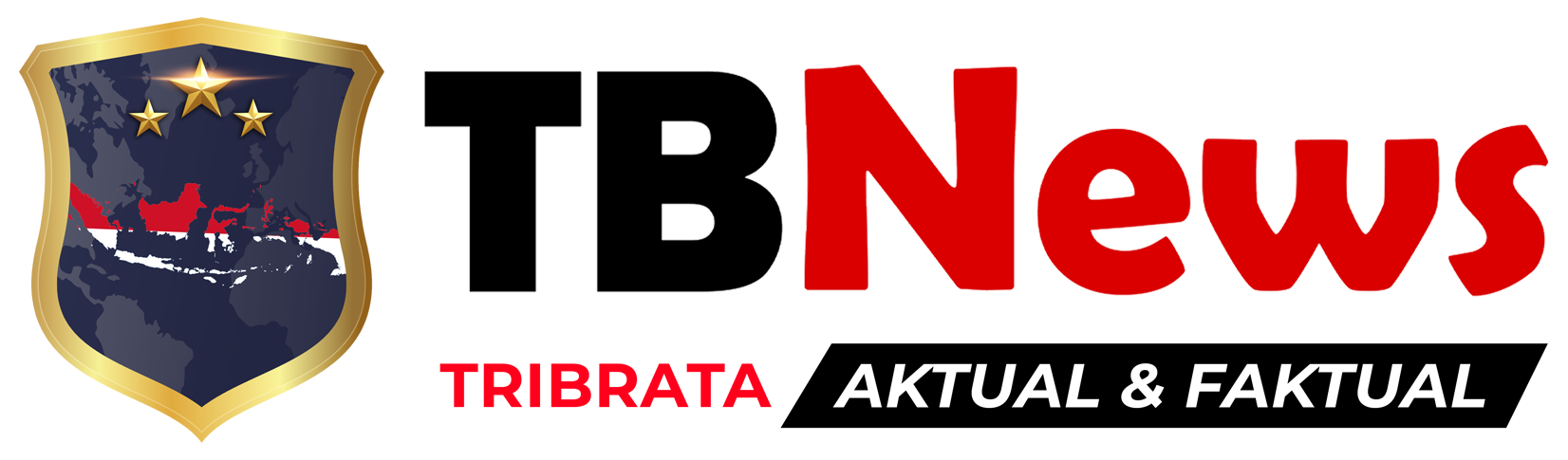Oleh : Ibnu Mazjah, SH, MH
Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut secara tegas diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Sebagai negara hukum (rechstaat), maka supremasi hukum sejatinya merupakan denyut jantung yang menjadi landasan paling mendasar dalam hal pelaksanaan pembangunan nasional.
Hukum sebagai sebuah tatanan tertib manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat sejatinya terdiri dari hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dalam arti sempit, hukum didefinikasikan sebagai hukum tertulis yang berlaku sebagai hukum positif dan tertuang di dalam bentuk peraturan perundangan-undangan (ius constitutum). Sedangkan dalam arti luas, hukum adalah tatanan norma yang mengatur perilaku manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat.
Dalam proses perjalanannya, hukum tidak tertulis berupa tatanan norma yang juga hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat itu kemudian pada gilirannya memberikan warna terhadap perkembangan dunia dalam bidang hukum itu sendiri. Merujuk kepada teori seorang tokoh hukum beraliran positivisme, Hans Kelsen tentang teori grundnorm yang begitu fenomenal di kalangan para juris, mengungkapkan, setiap norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu mendasarkan validitasnya dari norma lainnya yang lebih tinggi. Artinya, norma itu terbentuk dari norma lainnya yang lebih tinggi lagi. Begitupun seterusnya hingga pada akhirnya sampailah kepada norma tertinggi (grundnorm).
Di Indonesia, grundnorm itu adalah Pancasila. Pancasila terbentuk dari berbagai norma yang berlaku di masyarakat, seperti adat istiadat, hukum adat, serta norma-norma lainnya, bahkan hingga norma agama. Karena itulah, filsafat hukum dari bangsa Indonesia yang membentuk segala peraturan hukum dan perundang-undang sejatinya adalah filsafat Pancasila.
Apa yang diungkapkan Kelsen tentang grundnorm tersebut, layak menjadi pisau analisa terhadap berbagai tragedi hukum di negeri ini. Betapa tidak, sejumlah ironi hukum menyangkut perilaku penyelenggara negara maupun para penegak hukum dapat terjadi karena isu tentang penegakan etika lebih redup dibandingkan dengan persoalan penegakan hukum yang bersifat tertulis selama ini. Padahal, harus disadari tatanan moral dan penegakan etika hukum jauh lebih luhur dibandingkan dengan persoalan penegakan hukum yang bersifat tertulis.
Di lain pihak, dalam kerangka berpikir hukum yang terlalu terpaku pada persoalan legalitas formal, sejumlah tindakan yang patut dianggap sebagai sebuah pelanggaran norma, tak mampu dijangkau melalui instrumen hukum positif kita. Karena itu lah, di berbagai organisasi, institusi maupun lembaga penyelenggara negara, penguatan lini etika dan moral ke dalam bentuk sebuah aturan yang dituangkan melalui suatu code of conduct tersendiri, mutlak diperlukan. Terlebih di lembaga penegak hukum, hal tersebut diperlukan agar tidak sampai terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan (abuse of power).
Sekadar flash back ke belakang, beberapa peristiwa hukum yang mencuat ke ruang publik beberapa bulan lalu, satu diantaranya adalah penetapan status Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Penetapan tersangka secara tiba-tiba di saat Komjen Budi Gunawan secara resmi dicalonkan sebagai Kapolri, tak pelak mengundang banyak pertanyaan. Meskipun, KPK memberikan argumen, penyelidikan terhadap Komjen Budi Gunawan, telah berlangsung sejak Juli 2014, namun alasan tersebut secara faktual tak serta merta menjamin kepercayaan publik, menyangkut adanya faktor non yuridis dalam kaitannya dengan penetapan tersangka itu.
Dari situ, muncul beberapa isu hukum yang perlu dicatat. Pertama, terkait penyelidikan yang dilakukan terhadap Komjen Budi Gunawan, publik memang tak mampu menjangkau kewenangan KPK dalam hal penyelidikan yang dilakukan, karena lazimnya upaya penyelidikan bersifat tertutup. Ke dua, bagaimana dengan laporan terkait rekening dengan jumlah tak wajar perwira tinggi Polri maupun penyelenggara negara lainnya yang telah dikantongi KPK ?
Menjadi terkesan janggal, ketika hanya Komjen Budi Gunawan yang saat itu menjadi calon Kapolri yang tiba-tiba “dikebut” proses hukumnya hingga menjadi tersangka. Sementara, publik tidak mengetahui, bagaimana dengan laporan hasil analisis (LHA) PPATK lainnya yang juga telah diserahkan ke lembaga superbody itu.
Secara normatif, ke dua isu hukum itu memang menjadi kewenangan atribusi KPK yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang KPK. Masalah standar dua alat bukti dalam hal penetapan tersangka, yang dipersoalkan kubu Komjen Budi Gunawan, itu soal lain. Meskipun, saat itu, KPK mengklaim penetapan tersebut telah memenuhi prosedur adanya dua alat bukti sesuai KUHAP.
Pada situasi tersebut, dalam konteks hukum formil, sejatinya telah terjadi kesenjangan antara positifitas (hukum yang berlaku) dengan realitas sosial berupa sikap nurani hukum dari pihak kubu Komjen Budi Gunawan yang merasa terlanggar hak asasinya sebagai buntut dari penetapan tersangka yang dinilai sewenang-wenang, zonder mempertimbangkan standar alat bukti yang cukup.
Dalam praktik beracara yang lazim terjadi di negeri ini, menyangkut penilaian secara objektif berkenaan dengan keabsahan alat bukti yang paralel dengan keabsahan status penetapan tersangka, adalah melalui persidangan materi pokok perkara. Di situ lah titik ketegangan antara positifitas dengan realitas sosial, terjadi. Namun dari sudut pandang akademis, ketidakcukupan alat bukti terkait penetapan tersangka, tentu berimplikasi kepada hal yang menyangkut cacat kewenangan.
Sekadar membandingkan aturan hukum yang berlaku di beberapa negara, seperti Perancis dan Belanda, berkaitan dengan penetapan tersangka dan proses penilaian alat bukti, sebenarnya diakomodir melalui sidang pendahuluan dengan dipimpin hakim komisaris. Tetapi, bila dianalogikan dengan sidang praperadilan di Indonesia, kedudukan dan fungsi hakim komisaris di Belanda dan Juge d’instruction di perancis, tidak sebanding kewenangannya.
Praperadilan cenderung bersifat formalitas, yaitu jika pasal yang didakwakan termasuk delik yang pembuatnya dapat ditahan, maka langsung tuntutan ditolak. Padahal, mestinya diperiksa lebih lanjut, termasuk saksi dan alat bukti lain apakah pasal itu yang dilanggar atau apakah cukup alasan untuk menduga keras tersangka/terdakwa melakukan perbuatan yang disangkakan (Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Hal. 140). Bersambung (Bagian pertama dari dua tulisan)
* Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga [Redaktur Tribratanews.com]