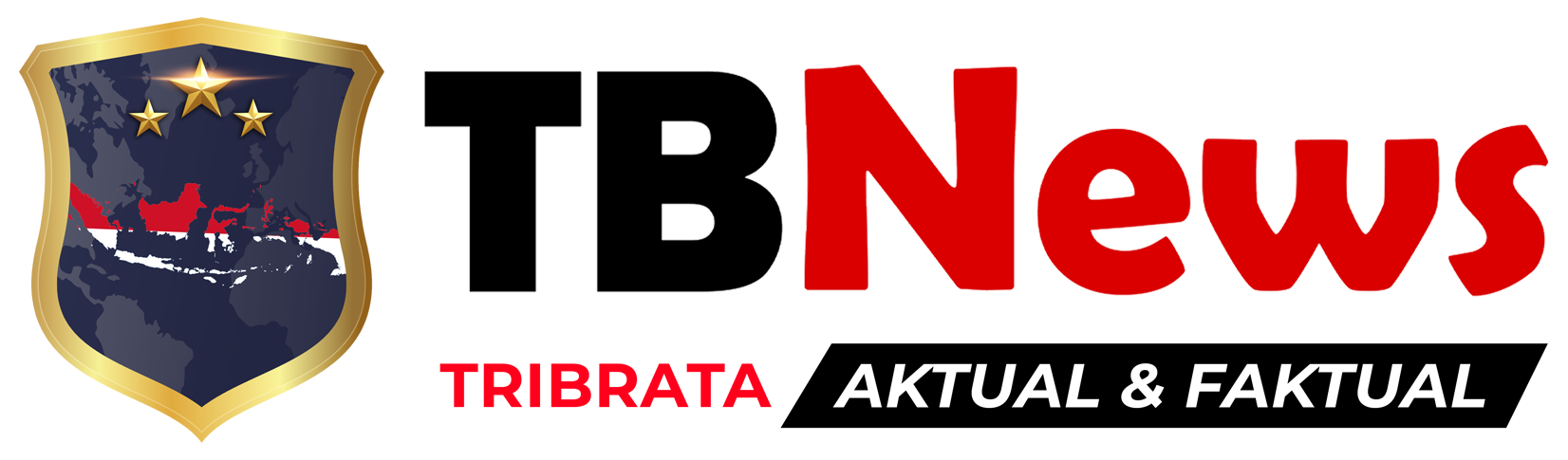Oleh : Ibnu Mazjah, S.H, M.H
Pemberantasan korupsi, setidaknya dalam satu dekade belakangan ini menjadi isu sentral dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Antusiasme rakyat terhadap persoalan penegakkan hukum utamanya korupsi tak pernah surut karena korupsi ibarat penyakit kronis yang menggerogoti bangsa ini hingga menyebabkan berbagai krisis multidimensi, seperti ekonomi, sosial, politik hingga budaya.
Pemberitaan tentang masalah korupsi di media massa setiap hari tak pernah henti menghiasi ruang pembaca. Kalangan penegak hukum yang kerap muncul di depan layar kaca, maupun di halaman media cetak dengan menampilkan segenap kinerja dalam mengungkap berbagai kasus korupsi bak primadona di kalangan khalayak.
Isu tentang pemberantasan korupsi memang menjadi suatu hal yang populis di tengah masyarakat. Karenanya, setiap langkah ataupun upaya pemerintah maupun DPR yang berkaitan dengan politik hukum tentang pemberantasan korupsi menjadi isu yang sensitif bila tak bersesuaian dengan penafsiran sebagian kalangan masyarakat di negeri ini. Siapapun paham, hal itu dikarenakan suatu postulat bahwa korupsi merupakan musuh bersama.
Karena itu, asumsi masyarakat yang menilai siapapun yang mencoba melakukan sebuah tindakan yang tidak sejalan dengan ide-ide yang dinilai progresif, dianggap tak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Tak terkecuali pihak eksekutif dan legislatif (baca, pemerintah dan DPR). Salah satu contoh terkait isu yang kini kian menghangat yakni berkaitan dengan rencana perubahan (revisi, red) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Isu pro kontra seputar pelaksanaan revisi undang-undang pun mencuat di media massa beberapa hari terakhir ini.
Betapapun runcingnya perdebatan serta pro-kontra rencana DPR menyangkut revisi undang-undang Komisi anti risuah yang telah menjadi agenda program legislasi nasional itu, namun, sepatutnya, upaya mencari solusi tetap tidak melupakan landasan filosofi kita sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) dan bukan sebagai negara berdasarkan kekuasaan (machstaat).
Hal itu karena ketentuan yang paling fundamental yang menegaskan Indonesia sebagai Negara hukum sejatinya telah diatur dalam UUD 1945 pasca perubahan yakni Pasal 1 ayat (3). Indonesia menganut konsep Negara hukum (rechstaat), sementara di luar itu ada pula yang menganut konsep rule of law, sebagai salah satu konsep yang juga eksis di dunia.
Konsep rechstaat bersumber pada sistem hukum civil law sistem yang merupakan warisan budaya hukum Eropa Continental, sementara rule of law berasal dari konsep common law system yang notabene bersumber dari warisan budaya hukum masyarakat Anglo Saxon.
Sebagai penganut sistem hukum Civil Law Sistem, peranan dan posisi aparat penegak hukum adalah sebagai penjaga undang-undang. Karena itu, dalam hal setiap pengambilan keputusan dan dalam hal melakukan tindakan oleh aparat penegak hukum harus memenuhi aspek legalitas yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini tentunya sejalan dengan konsep dan tujuan dari negara hukum itu sendiri, yakni tercapainya masyarakat tertib yang berkeadilan dalam kerangka menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia dari tindakan kesewenang-wenang aparat.
Konsep negara hukum tersebut, kiranya dapat dijadikan sebagai bahan refleksi yang dapat dijadikan acuan dalam menyikapi beberapa isu penting mengenai revisi UU KPK, khususnya masalah penyadapan. Kita sepakat, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diperangi jua dengan cara-cara yang luar biasa. Tetapi, dalam upaya memerangi musuh bersama tersebut, penegakan hukum seyogyanya juga tetap dilakukan tanpa melukai hukum ataupun mencederai asas yang sejatinya telah ada.
Hal ini tentunya demi mewujudkan sebuah proses pencarian keadilan yang berkepastian hukum dan bermartabat sehingga dapat menjamin hak-hak setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam tataran dogmatis, undang-undang No.30 Tahun 2002 secara jelas memberikan kewenangan artibusi kepada KPK untuk melakukan penyadapan. Kewenangan tersebut, dalam praktek law enforcement di negeri ini, tak dapat dipungkiri menjadi salah satu mata rantai vonis hakim di pengadilan yang menghukum para koruptor. Dan pada akhirnya, membongkar perkara-perkara korupsi melalui instrumen penyadapan kian populer dilakukan lembaga penegak hukum ad hoc tersebut. Lebih-lebih, dalam beberapa perkara, penyadapan yang dilakukan dalam tahap penyelidikan itu diperdengarkan kepada publik hingga diperdengarkan di ruang sidang pengadilan.
Tak pelak lagi, opini publik pun kian mendukung berbagai aksi penyadapan, menimbulkan suatu persepsi praktis, yang intinya untuk memberantas korupsi bisa dilakukan dengan segala cara. Alih-alih memberikan penguatan terhadap lembaga agar bertindak secara proporsional dalam kerangka penegakan hukum yang lebih bermartabat, isu soal penyadapan yang menjadi agenda dalam rencana revisi undang-undang KPK tersebut dituding sebagai salah satu upaya pelemahan terhadap lembaga super body itu.
Tudingan itu, wajar saja mengemuka. Sebab, revisi terkait ketentuan soal penyadapan, dinilai para penggiat anti korupsi bakal mempreteli salah satu kewenangan strategis yang dimiliki KPK yang pada akhirnya berpihak pada koruptor.
Kendatipun demikian, penulis mencoba melepaskan penilaian yang kami anggap subjektif tersebut dalam pembahasan tulisan ini. Sebaliknya, justeru pengaturan dan prosedur yang lebih ketat dalam hal melakukan penyadapan diperlukan, mengingat, peran dan tantangan KPK dalam hal penegakan hukum ke depan kian besar.
Sebab peran KPK yang sangat strategis ke depan membawa implikasi, kebutuhan akan sebuah pembenahan birokrasi lembaga tersebut sebagai persoalan yang krusial dan mendesak. Khususnya berkaitan dengan tata kelola penggunaan kewenangan yang sejalan dengan due proses of law. [Tulisan pertama dari dua tulisan/bersambung]
* penulis adalah redaktur www.tribratanews.com